Catatan penerjemah: berikut ini saya hadirkan terjemahan tidak resmi dari teks 5 dubia yang disiapkan oleh empat kardinal. Perbuatan empat kardinal tersebut merupakan tindakan historis yang baru terjadi lagi sejak abad pertengahan, yaitu ketika para teolog dari universitas ternama di Eropa berusaha mengoreksi Paus Yohanes XXII.
Ini bukanlah hal yang patut kita abaikan. Karena Uskup Roma saat ini, Penerus St. Petrus, yang memiliki mandat untuk menjadi pemersatu dan menguatkan iman saudara-saudarinya, dalam aspek ini dapat dikatakan gagal dalam memenuhi misi yang dipercayakan kepadanya. Konsekuensinya adalah kekacauan dan kebingungan di antara umat beriman, serta timbulnya konflik penafsiran antara sesama teolog, uskup dan konferensi para uskup.
Lama sesudah 5 dubia ini, akhirnya diterbitkan juga filial correction – koreksi dari anak-anak kepada bapanya, yang ditandatangani oleh terutama para teolog yang tersebar di seluruh dunia (walau ada pula mereka yang bukan teolog namun ikut menandatangani surat filial correction). Kardinal Burke pernah menjanjikan dikeluarkannya koreksi formal, yang diduga merupakan koreksi yang diberikan beberapa kardinal. Namun hingga saat ini belum ada pemberitaan terkait hal tersebut.
Kendati demikian, kita tidak perlu merasa panik ataupun takut secara berlebihan. Kita juga tidak perlu menghina, menjelek-jelekkan, atau pun membenci Wakil Kristus saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan tetap ada dan tinggal dalam bahtera, sekalipun tampaknya Ia sedang tidur. Apa yang mesti menjadi tugas kita ialah memperdalam wahyu Allah yang disampaikan melalui Kitab Suci dan Tradisi, selalu dalam bimbingan Magisterium Gereja dan dalam terang Roh Kudus. Atas alasan inilah saya menerjemahkan teks 5 dubia tersebut, dengan harapan agar teks ini dapat merangsang keinginan studi yang lebih mendalam dan serius mengenai ajaran iman kita, dan khususnya yang terkait dengan moralitas.
Saya juga hendak mengumumkan bahwa untuk saat ini, konten Lux Veritatis 7 selanjutnya akan terpusat pada ajaran moral Katolik, yang mana saya akan menghadirkan beberapa tamu yang sekaligus adalah guru yang terjamin kesetiaannya terhadap Magisterium (baca: maksudnya saya hendak menerjemahkan teks-teks dari Father Wojciech Giertych OP (teolog pribadi Paus yang juga teolog moral), Kardinal Ratzinger, Kardinal Caffarra, Kardinal Burke, dst) dan konsekuensinya untuk sementara tidak akan ada konten mengenai liturgi.
Akhir kata, ini adalah awal dan arahan baru dari perjalanan blog ini. Mari kita tekun dalam berdoa, belajar, dan bekerja.
+++
1. Sebuah Pengantar yang Perlu
Pengiriman surat kepada Bapa Suci Paus Fransiskus oleh empat kardinal berasal dari keprihatinan pastoral yang mendalam.
Kami memperhatikan adanya disorientasi serius dan kekacauan besar di antara banyak umat beriman mengenai perkara yang amat penting dalam kehidupan Gereja. Kita memperhatikan bahwa bahkan di dalam kolega episkopal terdapat penafsiran yang saling berlawanan terhadap bab 8 “Amoris Laetitia”.
Tradisi agung Gereja mengajarkan kita bahwa jalan keluar dari situasi ini ialah kembali pada Bapa Suci, meminta Takhta Apostolik untuk menyelesaikan keraguan-keraguan ini yang merupakan penyebab disorientasi dan kekacauan.
Tindakan kami, oleh sebab itu, berlandaskan keadilan dan kasih.
Berlandaskan keadilan: melalui inisiatif kami, kami mengakui bahwa pelayanan Petrus adalah pelayanan kesatuan, dan kepada Petrus, kepada Paus, tercakup pelayanan untuk menegaskan dalam iman.
Berlandaskan kasih: kami ingin membantu Paus mencegah perpecahan dan konflik di dalam Gereja, meminta kepadanya untuk menjernihkan ambiguitas.
Kami juga telah melaksanakan sebuah tugas khusus. Menurut Kitab Hukum Kanonik (349), kepada para kardinal, bahkan bila dianggap secara individual, dipercayakan tugas membantu Paus dalam merawat Gereja universal.
Bapa Suci telah memutuskan untuk tidak menanggapi. Kami menafsirkan keputusannya yang berdaulat sebagai undangan untuk melanjutkan refleksi dan diskusi, dengan tenang dan penuh hormat.
Maka kami menginformasikan seluruh umat Allah mengenai inisiatif kami dan menyajikan semua dokumentasi.
Kami berharap tak seorang pun menafsirkan perkara ini seturut paradigma “progresif/konservatif”. Ini tidak sesuai tujuan kami. Kami sungguh peduli terhadap kebaikan jiwa-jiwa sejati, hukum tertinggi Gereja, dan bukan tentang mendukung bentuk politik apapun di dalam Gereja.
Kami berharap tak satu pun akan menghakimi kami secara tidak adil sebagai musuh Bapa Suci dan orang-orang yang tak memiliki belas kasih. Apa yang telah dan sedang kami lakukan berasal dari afeksi kolegial mendalam yang menyatukan kami dengan Paus, dan dari keprihatinan terhadap kebaikan umat beriman.
Kard. Walter Brandmüller
Kard. Raymond L. Burke
Kard. Carlo Caffarra
Kard. Joachim Meisner
2. Surat Empat Kardinal kepada Paus
Kepada Bapa Suci Paus Fransiskus
dan untuk perhatian Yang Utama Kardinal Gerhard L. Müller
Bapa Suci yang terkasih,
Sesudah penerbitan Anjuran Apostolik anda berjudul “Amoris Laetitia”, para teolog dan cendekiawan telah mengajukan penafsiran yang tidak hanya menyimpang, tetapi juga bertentangan, terutama terkait bab 8. Terlebih, media telah menekankan perdebatan ini, dan karenanya memprovokasi ketidakpastian, kekacauan, dan disorientasi di antara banyak umat beriman.
Karena hal ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tetapi juga banyak Uskup dan Imam, telah menerima sejumlah permohonan dari umat beriman yang berasal dari berbagai strata sosial mengenai pemberian penafsiran yang tepat dari bab 8 Anjuran Apostolik tersebut.
Kini, didesak dalam hati nurani oleh tanggung jawab pastoral kami dan keinginan untuk kian menerapkan sinodalitas yang mana Bapa Suci mendesak kami, maka kami, dengan rasa hormat mendalam, kami mengizinkan diri untuk bertanya kepadamu, Bapa Suci, sebagai Guru Iman yang Tertinggi, yang dipanggil Tuhan yang bangkit untuk menguatkan saudara-saudaranya dalam iman, untuk menyelesaikan ketidakpastian dan membawa kejernihan, dengan menanggapi secara baik “Dubia” yang kami lampirkan di surat ini.
Semoga Bapa Suci berkehendak untuk memberkati kami, sebagaimana kami berjanji untuk terus menerus mengingatmu dalam doa.
Kard. Walter Brandmüller
Kard. Raymond L. Burke
Kard. Carlo Caffarra
Kard. Joachim Meisner
Rome, 19 September 2016
3. “Dubia”
- Setelah afirmasi “Amoris Laetitia” (no. 300-305), apakah kini menjadi mungkin untuk memberikan absolusi dalam Sakramen Tobat dan karenanya mengizinkan pemberian Komuni Suci kepada seseorang yang hidup bersama dengan orang berbeda “more uxorio” (layaknya pasangan yang menikah) kendati masih terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, tanpa memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam “Familiaris Consortio” no. 84 dan yang selanjutnya ditegaskan dalam “Reconciliatio et Paenitentia” no. 34 dan “Sacramentum Caritatis” no. 29. Dapatkah ungkapan “dalam kasus-kasus tertentu” sebagaimana ditemukan dalam catatan kaki 351 (AL 395) dari Anjuran “Amoris Laetitia” diterapkan bagi orang-orang yang bercerai yang berada dalam persatuan baru dan yang terus hidup dalam kondisi “more uxorio”?
- Setelah penerbitan Anjuran Apostolik “Amoris Laetitia” (bdk. No. 304), apakah seseorang masih perlu menanggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 79 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, mengenai keberadaan norma moral absolut yang melarang perbuatan-perbuatan yang secara intrinsik jahat (intrinsically evil acts) dan yang mengikat tanpa pengecualian?
- Setelah “Amoris Laetitia” (No. 301), apakah masih mungkin untuk menegaskan bahwa seseorang yang secara habitual menjalani hidup yang bertentangan dengan perintah hukum Allah, misalnya hukum yang melarang perzinahan (bdk. Mt 19:3-9), mendapati dirinya berada dalam situasi objektif dosa berat habitual (bdk. Pontifical Council for Legislative Texts, Declaration, June 24, 2000)?
- Setelah penegasan “Amoris Laetitia” (No. 302) mengenai “situasi-situasi yang meringankan tanggung jawab moral”, apakah seseorang masih perlu menganggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 81 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, yang menurut keduanya “situasi atau intensi tidak pernah bisa mengubah sebuah perbuatan yang secara intrinsik jahat, oleh karena objeknya, menjadi perbuatan yang baik “secara subjektif” atau dapat dibela sebagai sebuah pilihan”?
- Setelah “Amoris Laetitia” (No. 303) apakah seseorang masih perlu menganggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 56 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, yang mengecualikan penafsiran kreatif mengenai peran hati nurani dan yang menekankan bahwa hati nurani tidak pernah bisa diberi wewenang untuk melegitimasi pengecualian terhadap norma-norma moral absolut yang melarang perbuatan-perbuatan yang secara intrinsik jahat oleh karena objeknya?
4. Catatan Penjelasan dari Empat Kardinal
KONTEKS
“Dubia” (dari kata Latin: “keraguan”) adalah pertanyaan formal yang diajukan di hadapan Paus dan Kongregasi Ajaran Iman, yang meminta klarifikasi atas isu-isu tertentu mengenai doktrin atau praktik.
Apa yang khusus dari pertanyaan ini ialah ia disusun sedemikian rupa sehingga mengharuskan jawaban “ya” atau “tidak”, tanpa argumentasi teologis. Cara berbicara di hadapan Takhta Apostolik ini bukanlah ciptaan kami, ini adalah praktik yang berusia tua.
Mari kita langsung ke pokok yang dipersoalkan
Setelah penerbitan Anjuran Apostolik “Amoris Laetitia” mengenai kasih dalam keluarga, sebuah perdebatan telah muncul secara khusus mengenai bab delapannya. Di sini secara khusus paragraf 300-305 telah menjadi objek penafsiran yang menyimpang.
Bagi banyak pihak – para uskup, imam, umat beriman – paragraf tersebut menyinggung atau bahkan secara eksplisit mengajarkan sebuah perubahan dalam disiplin Gereja berkenaan dengan mereka yang bercerai yang sedang menjalani hidup dalam persatuan baru, kendati yang lain, walau mengakui kurangnya kejelasan atau bahkan ambiguitas dari pasase yang dibicarakan, tetap berargumen bahwa halaman yang sama ini dapat dibaca dalam kesinambungan dengan magisterium sebelumnya dan tidak mengandung perubahan dalam praktik dan ajaran Gereja.
Didorong oleh keprihatian pastoral bagi umat beriman, empat kardinal telah mengirim surat kepada Bapa Suci dalam bentuk “Dubia”, sembari berharap untuk menerima kejelasan, lantaran keraguan dan ketidakpastian selalu amat berbahaya bagi kepedulian pastoral.
Fakta bahwa para penafsir tiba pada kesimpulan berbeda disebabkan karena cara-cara memahami kehidupan moral Kristiani yang menyimpang. Dalam pengertian ini, yang dipertaruhkan dalam “Amoris Laetitia” bukan hanya persoalan tentang apakah mereka yang bercerai yang telah memasuki persatuan baru boleh atau tidak – dalam situasi tertentu – diizinkan kembali untuk menerima sakramen-sakramen.
Melainkan, penafsiran dokumenvtersebut juga mengimplikasikan pendekatan yang berlawanan dan berbeda terhadap gaya hidup Kristiani.
Jadi, kendati pertanyaan pertama “Dubia” terkait dengan pertanyaan praktis tentang mereka yang bercerai dan menikah secara sipil, empat pertanyaan lainnya menyentuh pokok mendasar dari kehidupan Kristiani.
BEBERAPA PERTANYAAN
Dubia no. 1
Setelah afirmasi “Amoris Laetitia” (no. 300-305), apakah kini menjadi mungkin untuk memberikan absolusi dalam Sakramen Tobat dan karenanya mengizinkan pemberian Komuni Suci kepada seseorang yang hidup bersama dengan orang berbeda “more uxorio” (layaknya pasangan yang menikah) kendati masih terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, tanpa memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam “Familiaris Consortio” no. 84 dan yang selanjutnya ditegaskan dalam “Reconciliatio et Paenitentia” no. 34 dan “Sacramentum Caritatis” no. 29. Dapatkah ungkapan “dalam kasus-kasus tertentu” sebagaimana ditemukan dalam catatan kaki 351 (AL 395) dari Anjuran “Amoris Laetitia” diterapkan bagi orang-orang yang bercerai yang berada dalam persatuan baru dan yang terus hidup dalam kondisi “more uxorio”?
Pertanyaan 1 membuat rujukan khusus kepada “Amoris Laetitia” no. 305 and catatan kaki 351. Walau catatan kaki 351 secara spesifik berbicara tentang sakramen tobat dan Komuni, ia tidak menyebutkan mereka yang bercerai dan menikah kembali secara sipil dalam konteks ini, tidak pula dalam teks utama.
Anjuran Apostolik “Familiaris Consortio” Paus Yohanes Paulus II no. 84 sudah merenungkan kemungkinan mengizinkan mereka yang bercerai dan menikah kembali secara sipil untuk menerima sakramen-sakramen. Ia menyebutkan tiga syarat:
- Orang yang bersangkutan tidak dapat berpisah tanpa melakukan ketidakadilan baru (misalnya, mereka mungkin bertanggung jawab membesarkan anak-anak mereka);
- Mereka mengemban komitmen untuk hidup seturut kebenaran situasi mereka, yaitu, mereka berhenti menjalani hidup bersama seakan-akan mereka adalah suami dan istri (“more uxorio”), dan berpantang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang pantas bagi pasutri;
- Mereka menghindar dari memberikan skandal (yaitu, mereka mengelak dari memberikan penampilan dosa guna menghindari bahaya menuntun orang lain ke dalam dosa).
Syarat-syarat yang disebutkan “Familiaris Consortio” no. 84 dan yang diingat oleh dokumen-dokumen selanjutnya akan segera tampak masuk akal ketika kita mengingat bahwa persatuan perkawinan tidak sekadar berlandaskan rasa saling afeksi dan bahwa perbuatan-perbuatan seksual bukan sekadar satu aktivitas di antara aktivitas lain yang dilakukan pasangan suami istri.
Relasi-relasi seksual itu dimaksudkan untuk cinta perkawinan. Mereka begitu penting, begitu baik dan berharga, sehingga mereka membutuhkan konteks khusus, konteks cinta perkawinan. Oleh sebab itu, tidak hanya mereka yang bercerai lalu menikah kembali perlu berpantang, tetapi juga setiap orang yang tidak menikah. Bagi Gereja, perintah keenam “Jangan berzinah” selalu mencakup setiap penggunaan seksualitas manusia yang tidak hanya bersifat perkawinan yaitu, perbuatan seksual apapun selain yang dilakukan mereka terhadap mempelainya yang sah.
Dengan mengizinkan pemberian Komuni kepada umat beriman yang berpisah atau bercerai dari pasangan sah mereka dan yang telah memasuki persatuan baru tempat mereka hidup bersama dengan orang lain seakan-akan sebagai suami dan istri, maka, melalui praktiknya, tampaknya Gereja mengajarkan satu dari sekian penegasan berikut terkait pernikahan, seksualitas manusia, dan hakikat sakramen (catatan penerjemah: tiga poin berikut adalah ajaran yang salah, yang berasal dari konsekuensi pemberian Komuni bagi mereka yang bercerai dan menikah lagi):
- Mereka yang bercerai tidak melenyapkan ikatan perkawinannya, dan pasangan dalam persatuan baru ini tidaklah menikah. Namun, mereka yang tidak menikah, dalam situasi tertentu, dapat secara sah terlibat dalam perbuatan seksual yang intim.
- Mereka yang bercerai melenyapkan ikatan perkawinan. Mereka yang tidak menikah tidak bisa secara sah terlibat dalam perbuatan seksual. Mereka yang bercerai dan menikah kembali adalah pasangan yang sah dan perbuatan seksual mereka adalah perbuatan perkawinan yang sah.
- Sebuah perceraian tidak meleyapkan ikatan perkawinan, dan pasangan dalam persatuan baru tidaklah menikah. Mereka yang tidak menikah, tidak bisa secara sah terlibat dalam perbuatan seksual, sehingga mereka yang bercerai dan menikah kembali secara sipil hidup dalam situasi dosa berat yang objektif, publik, dan habitual. Meskipun demikian, mengizinkan seseorang menerima Ekaristi tidak berarti bahwa Gereja menyetujui status hidup publik mereka; umat beriman dapat mendekati meja Ekaristi bahkan dengan kesadaran akan dosa berat, dan menerima absolusi dalam sakramen tobat tidak selalu harus mensyaratkan tujuan memperbaiki hidup. Sakramen-sakramen, oleh sebab itu, diceraikan dari kehidupan: ritus-ritus dan ibadat Kristiani ada dalam bentuk yang berbeda secara utuh daripada kehidupan moral Kristiani.
Dubia no. 2
Setelah penerbitan Anjuran Apostolik “Amoris Laetitia” (bdk. No. 304), apakah seseorang masih perlu menanggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 79 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, mengenai keberadaan norma moral absolut yang melarang perbuatan-perbuatan yang secara intrinsik jahat (intrinsically evil acts) dan yang mengikat tanpa pengecualian?
Pertanyaan kedua berkaitan dengan keberadaan apa yang disebut perbuatan yang secara intrinsik jahat. Ensiklik Yohanes Paulus II “Veritatis Splendor” no. 79 menyatakan bahwa seseorang dapat “mencirikan sebagai hal yang jahat secara moral seturut jenisnya… pilihan bebas terhadap beberapa perilaku atau perbuatan spesifik jenis tertentu, yang terpisah dari pertimbangan intensi yang mana pilihan dibuat atau totalitas konsekuensi yang dapat diprediksi dari tindakan itu bagi semua orang yang bersangkutan.”
Jadi, ensiklik tersebut mengajarkan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang selalu jahat, yang dilarang oleh norma-norma moral yang mengikat tanpa pengecualian (“moral absolut”). Norma moral absolut ini selalu negatif, yang artinya, ia memberitahu kita apa yang tidak semestinya kita lakukan. “Jangan membunuh.” “Jangan berbuat zinah.” Hanya norma negatif yang mengikat tanpa pengecualian.
Menurut “Veritatis Splendor”, terkait perbuatan yang secara intrinsik jahat, tidaklah diperlukan discernment situasi dan intensi. Menyatukan diri dengan wanita yang menikahi orang lain merupakan dan tetap termasuk perbuatan zinah yang semestinya tidak pernah dilakukan, bahkan bila dengan melakukannya sang pelaku mungkin dapat mengeluarkan rahasia-rahasia berharga dari kejahatan istri guna menyelamatkan kerajaan (apa yang terdengar seperti contoh dari film James Bond sudah direnungkan St. Thomas Aquinas dalam De Malo”, q. 15, a. 1). Yohanes Paulus II berargumen bahwa intensi (katakanlah, “menyelamatkan kerajaan”) tidak mengubah jenis perbuatan (di sini: “berbuat zinah”) dan bahwa cukuplah mengetahui jenis perbuatan tersebut (“berzinah”) guna mengetahui bahwa seseorang tidak semestinya melakukan itu.
Dubia no. 3
Setelah “Amoris Laetitia” (No. 301), apakah masih mungkin untuk menegaskan bahwa seseorang yang secara habitual menjalani hidup yang bertentangan dengan perintah hukum Allah, misalnya hukum yang melarang perzinahan (bdk. Mt 19:3-9), mendapati dirinya berada dalam situasi objektif dosa berat habitual sin (bdk. Pontifical Council for Legislative Texts, Declaration, June 24, 2000)?
Dalam paragraf 301 “Amoris Laetitia” mengingat bahwa: “Gereja memiliki tubuh refleksi yang kokoh mengenai faktor-faktor dan situasi-situasi yang meringankan tanggung jawab personal.” Dan paragraf tersebut menyimpulkan bahwa “dengan demikian tidak dapat lagi sekadar dikatakan bahwa mereka semua yang berada dalam situasi “ireguler” sedang hidup dalam kondisi berdosa berat dan tidak memiliki rahmat pengudusan.”
Dalam Deklarasinya tertanggal 24 Juni 2000, Pontifical Council for Legislative Texts berupaya mengklarifikasi KHK 915, yang menyatakan bahwa mereka yang “dengan keras kepala bertahan dalam dosa berat yang tampak, tidak semestinya menerima Komuni Suci.” Deklarasi tersebut berargumen bahwa kanon ini berlaku juga bagi umat beriman yang bercerai dan menikah lagi secara sipil. Ia menerangkan bahwa “dosa berat” harus dipahami secara objektif, sembari menimbang bahwa pelayan Ekaristi tidak memiliki sarana untuk menghakimi imputabilitas (catatan penerjemah: mungkin imputabilitas dapat diartikan sebagai kebersalahan atau tanggung jawab) subjektif dari seseorang.
Jadi, bagi Deklarasi tersebut, persoalan tentang memberikan sakramen-sakramen berkenaan dengan menilai situasi hidup objektif seseorang dan bukan tentang menghakimi apakah pribadi ini ada dalam kondisi berdosa berat. Secara subjektif ia barangkali tidak secara penuh bertanggung jawab atau mungkin tidak bertanggung jawab sama sekali.
Sejalan dengan itu, dalam ensikliknya “Ecclesia de Eucharistia” no. 37, St. Yohanes Paulus II mengingat bahwa “penilaian akan kondisi berahmat seseorang jelas sekali hanya milik orang yang bersangkutan, karena ini persoalan tentang memeriksa hati nurani seseorang.” Jadi, distingsi yang diacu oleh “Amoris Laetitia” antara situasi dosa berat subjektif dan situasi dosa berat objektif sungguh telah ditetapkan dengan baik dalam ajaran Gereja.
Namun Yohanes Paulus II meneruskan lewat desakan bahwa “dalam kasus-kasus perilaku lahiriah yang secara serius, jelas, dan kukuh bertentangan dengan norma moral, Gereja, dalam kepedulian pastoralnya terhadap ketentraman komunitas dan berlandaskan rasa hormat kepada sakramen, pasti merasa terlibat secara langsung.” Lantas ia mengulangi ajaran Kanon 915 yang disebutkan di atas.
Pertanyaan Dubia 3, dengan demikian, hendak mengklarifikasi, apakah setelah “Amoris Laetitia”, masih mungkin untuk berkata bahwa seseorang yang secara habitual hidup dalam kontradiksi dengan perintah hukum Allah, seperti perintah yang terkait dengan perzinahan, pencurian, pembunuhan, atau sumpah palsu, apakah mereka hidup dalam situasi dosa berat habitual secara objektif, bahkan bila, untuk alasan apapun, tidaklah pasti apakah secara subjektif mereka bersalah atasu pelanggaran habitual mereka.
Dubia no. 4
Setelah penegasan “Amoris Laetitia” (No. 302) mengenai “situasi-situasi yang meringankan tanggung jawab moral”, apakah seseorang masih perlu menganggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 81 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, yang menurut keduanya “situasi atau intensi tidak pernah bisa mengubah sebuah perbuatan yang secara intrinsik jahat, oleh karena objeknya, menjadi perbuatan yang baik “secara subjektif” atau dapat dibela sebagai sebuah pilihan”?
Dalam paragraf 302, “Amoris Laetitia” menekankan bahwa perihal situasi-situasi yang meringankan “penilaian negatif tentang situasi objektif tidak mengimplikasikan penilaian tentang imputabilitas atau kulpabilitas seseorang yang terkait.” Dubia mengacu kepada ajaran Gereja sebagaimana diungkapkan dalam “Veritatis Splendor” Yohanes Paulus II, yang menurutnya situasi atau niat baik tidak pernah bisa mengubah perbuatan yang secara intrinsik jahat menjadi dapat dibenarkan atau bahkan menjadi perbuatan baik.
Pertanyaan muncul apakah “Amoris Laetitia” juga, setuju bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum Allah, seperti perzinahan, pembunuhan, pencurian, atau sumpah palsu, tidak pernah bisa, atas dasar situasi yang meringankan tanggung jawab personal, menjadi dapat dibenarkan atau bahkan menjadi perbuatan baik.
Apakah perbuatan-perbuatan ini, yang oleh Tradisi Gereja disebut sebagai buruk dalam dirinya dan dosa berat, terus bersifat destruktif dan membahayakan siapapun yang melakukannya dalam status tanggung jawab moral subjektif apapun dalam diri mereka?
Atau, dapatkah perbuatan-perbuatan ini, sembari bergantung pada kondisi subjektif dan situasi serta niat, berhenti menjadi hal yang berbahaya dan dapat menjadi perbuatan terpuji atau setidaknya dapat dibenarkan?
Dubia no. 5
Setelah “Amoris Laetitia” (No. 303) apakah seseorang masih perlu menganggap ajaran St. Yohanes Paulus II dalam “Veritatis Splendor” no. 56 sebagai hal yang valid, ajaran yang berlandaskan Kitab Suci dan Tradisi Gereja, yang mengecualikan penafsiran kreatif mengenai peran hati nurani dan yang menekankan bahwa hati nurani tidak pernah bisa diberi wewenang untuk melegitimasi pengecualian terhadap norma-norma moral absolut yang melarang perbuatan-perbuatan yang secara intrinsik jahat oleh karena objeknya?
“Amoris Laetitia” no. 303 menyatakan bahwa “hati nurani dapat berbuat lebih dari sekadar mengakui bahwa situasi yang terberikan tidak selaras secara objektif dengan seluruh tuntutan Injil. Ia juga dapat mengakui dengan tulus dan jujur apa yang kini merupakan tanggapan paling murah hati yang dapat diberikan kepada Allah.” Dubia meminta klarifikasi mengenai pernyataan ini, terlepas bahwa mereka rentan terhadap penafsiran yang berlainan.
Bagi mereka yang mengajukan gagasan kreatif mengenai hati nurani, aturan-aturan hukum Allah dan norma hati nurani individu dapat berada dalam tegangan atau saling berlawanan, kendati keputusan terakhir harus dibuat hati nurani yang pada akhirnya memutuskan tentang baik atau buruk. Menurut “Veritatis Splendor” no. 56, “atas dasar ini, sebuah upaya dilakukan untuk melegitimasi apa yang disebut solusi “pastoral” yang berlawanan dengan ajaran Magisterium, dan untuk membenarkan sebuah penafsiran ‘kreatif’, yang menurutnya hati nurani moral sama sekali tidak diwajibkan, dalam setiap kasus, oleh sebuah aturan negatif khusus.”
Dalam perspektif ini, tidak akan pernah cukup bagi hati nurani moral untuk mengetahui “ini perzinahan” atau “ini pembunuhan” guna mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak seharusnya dilakukan seseorang.
Akan tetapi, seseorang juga perul melihat situasi atau niat untuk mengetahui bila tindakan ini tidak bisa dibenarkan atau diwajibkan (bdk. Pertanyaan 4 Dubia). Bagi teori-teori ini, hati nurani dapat dengan benar memutuskan bahwa dalam situasi tertentu, kehendak Allah bagi saya ialah melakukan perbuatan yang mana saya melanggar salah satu perintah-perintah-Nya. “Jangan berzinah” dipahami hanya sebagai norma umum. Kini dan sembari menimbang niat baik saya, berzinah ialah apa yang Allah haruskan dari saya. Dalam hal ini, kasus-kasus perzinahan yang berkebajikan, pembunuhan sah dan sumpah palsu yang wajib setidaknya dapat dipahami.
Ini berarti hati nurani dipahami sebagai fakultas yang secara otonom memutuskan tentang baik buruk sesuatu dan memahami hukum Allah sebabai beban yang dipaksakan sewenang-wenang dan terkadang dapat bertentangan dengan kebahagiaan sejati kita.
Meskipun demikian, hati nurani tidak memutuskan tentang baik dan buruk. Seluruh gagasan tentang “keputusan hati nurani” itu menyesatkan. Perbuatan hati nurani yang pas ialah menilai dan bukan memutuskan. Ia berkata “ini baik”, “ini buruk”. Kebaikan atau keburukan ini tidak bergantung padanya. Ia mengakui dan menyatakan kebaikan dan keburukan suatu perbuatan dan untuk melakukannya, untuk menilainya, hati nurani membutuhkan kriteria, ia secara inheren bergantung pada kebenaran.
Perintah-perintah Allah adalah pertolongan yang paling berkenan bagi hati nurani guna mengetahui kebenaran dan karenanya dapat menilai dengan tepat. Perintah-perintah Allah adalah ungkapan kebenaran tentang kebaikan kita, tentang keberadaan kita, menyingkapkan sesuatu yang krusial tentang cara menjalani hidup dengan baik. Paus Fransiskus juga mengungkapkan dirinya dalam kata-kata ini dalam “Amoris Laetitia” 295: “Hukum itu sendiri adalah karunia Allah yang menunjukkan jalan, karunia bagi setiap orang tanpa terkecuali.”


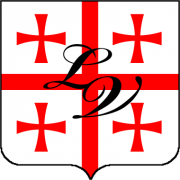














Yth. Sdr Admin.
Terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini. Selanjutnya, sebagai awam, saya berharap langkah-langkah yang perlu segera diambil dan dilaksanakan, mewakili Gereja Kudus di Indonesia dapat menentramkan hati umat sekalian.
Saya dengan penuh kesabaran akan terus menunggu kabar informasi perkembangannya melalui media ini serta turut mendoakan agar semua upaya selalu dalam pertolongan dan kasih Tuhan.
Terima kasih
…et cum spiritu tuo.
SukaSuka